PROFESIONALISME GURU
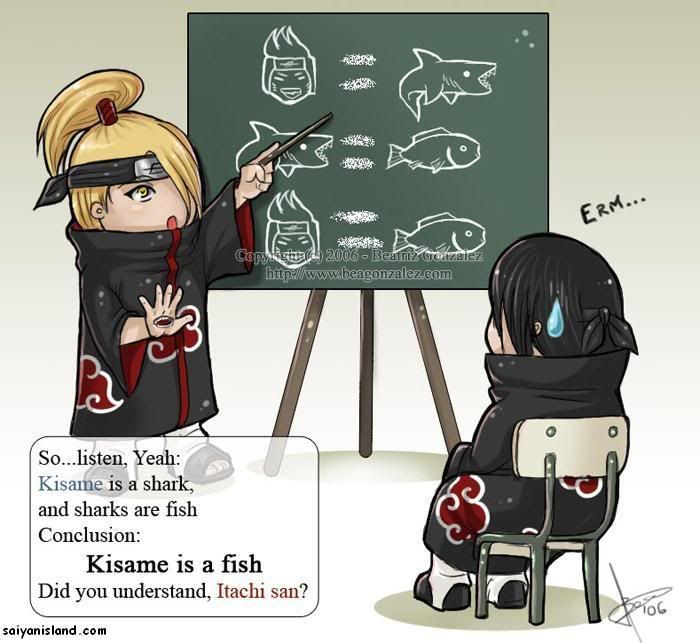 Profesionalisme merupakan komponen vital yang dapat menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, akan tetapi kenyataan yang ada pengembangan profesi masih dilakukan secara sporadik dan sentralistik. Dikatakan sporadik karena upaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan tidak dilakukan secara berkelanjutan, serta tidak diikuti evaluasi yang sistemik dan terencana. Dikatakan sentralistik karena upaya pengembangan diwarnai usaha penyeragaman pola dan materi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik guru dan tenaga kependidikan, sekolah maupun daerah.
Profesionalisme merupakan komponen vital yang dapat menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, akan tetapi kenyataan yang ada pengembangan profesi masih dilakukan secara sporadik dan sentralistik. Dikatakan sporadik karena upaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan tidak dilakukan secara berkelanjutan, serta tidak diikuti evaluasi yang sistemik dan terencana. Dikatakan sentralistik karena upaya pengembangan diwarnai usaha penyeragaman pola dan materi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik guru dan tenaga kependidikan, sekolah maupun daerah.Dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan yang melekat pada sistem yang ada, perlu dicarikan alternatif pemecahan supaya guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan profesi dan harkat diri secara wajar sesuai dengan akumulasi pengalaman hidup dan keahlian profesionalnya. Kegiatan yang dapat direalisasikan untuk menjamin profesionalisme guru agar senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kualitas layanan profesionalnya dari waktu kewaktu adalah dengan program sertifikasi yang berkelanjutan. Idealnya peningkatan profesionalisme diikuti oleh perbaikan sistim imbalan dan penjejangan karier dengan memperhitungkan imbalan progresif secara wajar sehingga dapat meningkatkan harkat diri guru sebagai pendidik.
Meskipun terdapat berbagai jenis perumusan tentang tugas dan kompetensi guru, akan tetapi secara nasional telah disepakati bahwa tugas tugas guru adalah seperti tercantum pada Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Tahun 2003 (pasal 39) bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Peran strategis guru sebagai pendidik berpengaruh langsung pada proses belajar mengajar siswa. Kualitas proses hasil belajar ini, pada akhirnya ditentukan oleh kualitas pertemuan antara guru dan siswa. Ilmu serta keterampilan yang dimilikinya akan menjadi alat pendewasaan anak didiknya, sehingga kualitas pendidikan lulusan suatu sekolah sering kali dipandang tergantung kepada peranan gurunya dan pengelolaan komponen yang terkait dalam proses KBM.
Menurut catatan Depdiknas, dari 1.141.168 guru SD se-Indonesia, ternyata baru 38 % atau 442.310 guru saja yang memenuhi syarat layak mengajar (Kompas, 25 Januari 2005). Mereka dikatakan tidak layak mengajar karena ijazah yang dimiliki di bawah jenjang D2 sehingga diasumsikan kreativitas, daya nalar, penguasaan ilmu dan kemampuan mengajar di kelas masih belum berkembang secara maksimal. Bahkan bagi guru-guru yang telah menempuh program penyetaraan dan memperoleh gelas D2 sekalipun, hal itu tidak serta merta menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan dalam mengajar di kelas. Permasalahan yang timbul kemudian adalah kurangnya tenaga guru untuk mata pelajaran umum, terutama mata pelajaran MIPA dan bahasa Inggris. Masalah ini memunculkan masalah berikutnya yaitu ketidaksesuaian keahlian dan mata pelajaran yang diajarkan (mismatch), di samping itu juga pembinaan tenaga guru juga dihadapkan pada masalah tingkat professional guru, baik substansi ilmu dalam mata pelajaran yang dipegang maupun kemampuan dan penguasaan metodologi. Tuntutan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Indonesia bersifat internal dan eksternal, baik fasilitas maupun kegiatan. Diakui atau tidak bahwa kekurangan-kekurangan itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kurangnya pihak sekolah dalam pengembangan profesionalisme para guru. Permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan merugikan pembangunan pendidikan nasional.
Berbagai gambaran dari struktur kepangkatan, pendidikan serta melaksanakan tugas, memberikan isyarat pentingnya upaya manajemen yang terus-menerus untuk meningkatkan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan. Sekalipun demikian, keberhasilan upaya manajemen tersebut terkait erat dengan sikap, perilaku, motivasi dan pribadi guru itu sendiri. Dalam dunia kerja, profesionalisme lebih banyak ditentukan oleh individu profesi yang bersangkutan. Berbeda dengan masa pendidikan, saat profesionalisasi lebih banyak ditentukan oleh lembaga pendidikan melalui aturan atau kaidah akademik yang digunakan sebagai standar oleh lembaga pendidikan. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan mutlak diperlukan.
Merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh P3TK Depdiknas (2003), sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata certification yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Apabila dihubungkan dengan profesi guru, maka sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.
Sertifikasi bagi guru merupakan cara yang efektif untuk menentukan kualitas guru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi mengajar. Sertifikasi bagi guru adalah sistem penilaian terpadu yang meliputi proses pengelolaan kinerja guru untuk menunjang peluang pengembangan karier profesionalnya. Sertifikasi guru diarahkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas, merit pay (pemberian imbalan yang baik bagi yang berprestasi), dan berkeadilan, dilakukan secara sistemik, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional.
Pengembangan profesionalisme guru dimulai dari kondisi objektif yang merupakan peta kemampuan profesional menuju ke arah standar kompetensi profesional guru dengan jaminan tertulis dalam bentuk sertifikat. Rasionalisasi perlunya sertifikasi bagi guru adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 39 sampai dengan No 44, globalisasi pendidikan dan pemberlakuan standar nasional pendidikan (PP. No. 15 Tahun 2005). Ruang lingkup sertifikasi guru sebagaimana ditegaskan dalam PP. No. 19 Tahun 2005 pada bab VI pasal 28 sebagaimana berikut: Pendidik harus memilki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memeilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (ayat 1). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijzah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru. Uji kompetensi tersebut dilakukan melalui penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan dengan menggunakan komponen portofolio sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Komponen portofolio tersebut meliputi; kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan dan keagamaan.
Sertifikasi memberikan jaminan akan kinerja dan kemampuan guru dalam melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara profesional. Tanpa sertifikasi akan semakin banyak orang merasa bisa menjadi guru tanpa melalui pendidikan yang disyaratkan. Anggapan bahwa pekerjaan guru dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki bekal kemampuan materi yang diperlukan harus segera diluruskan. Hakekat mengajar tidak sekedar transformasi ilmu semata tetapi ada unsur-unsur paedagogis sehingga terjadi perubahan perilaku anak didik baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.
Guru merupakan titik sentral kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Oleh itu profesionalisme guru merupakan suatu keharusan. Guru profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode, tapi juga harus mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas akan dunia pendidikan. Tetapi guru profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Pemahaman ini akan melandasi pola pikir dan pola kerja guru serta loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. Dalam implementasi proses belajar mengajar guru harus mampu mengembangkan budaya organisasi kelas, dan iklim organisasi pengajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 a). Guru yang profesional dipersyaratkan. Pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan paktis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada paktis pendidikan masyarakat Indonesia. Terakhir, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service training karena pertimbangan birokrasi yang kaku atau manajemen pendidikan yang masih lemah belum menyentuh dan mengangkat permasalahan di lapangan. in service training dapat dimulai dari program penyetaraan untuk meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan kemampuan-kemampuan yang sifatnya khusus melalui penataran, dan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk memperbaharui dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Melalui kegiatan sertifikasi dapat diketahui mana guru yang baik dan mana yang belum baik dilihat dari hasil penilaian terhadap kinerja guru termasuk kemampuan profesionalnya. Guru yang baik perlu dipertahankan keberadaannya jika perlu diberi penghargaan atau dipromosikan. Untuk guru yang belum baik perlu ditingkatkan kemampuannya melalui program penyetaraan, bimbingan, pelatihan dan penataran. Profesionalisme guru secara konsinten menjadi salah satu faktor terpenting dari kualitas pendidikan. Dalam studi-studi itu, guru yang profesional mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan lingkungan. Namun, untuk menghasilkan guru yang profesional juga bukanlah tugas yang mudah. Lebih-lebih untuk lembaga pendidikan yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perkembangan profesionalisme guru. Guru merupakan komponen yang layak mendapat perhatian karena baik ditinjau dari segi posisi yang ditempati dalam struktur organisasi pendidikan maupun dilihat dari tugas yang diemban, guru merupakan pelaksana terdepan yang menentukan dan mewarnai proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan umumnya.
Untuk itulah, melalui program sertifikasi ini dimungkinkan guru-guru profesional akan terlahir sebagai bentuk keinginan kita bersama dan bukan dimaknai sebagai program sporadik dan tidak sustainable. Melainkan sebagai program yang terencana yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme guru.
Mujakir
Pascasarjana UNY dan Mantan Direktur PUSMAJA Periode 2008-2009


